Artikel ini pertama kali tayang di Noisey.
Band-band legendaris sekalipun kadang mempunyai album jelek dalam katalog mereka. Kadang, sayangnya, album jelek yang menjadi perkenalanmu dengan sebuah band. Fenomena ini lumayan umum terjadi terutama sebelum era streaming musik via internet dimulai dan anda harus secara fisik mengunjungi toko musik dan mengambil risiko membeli album. Keputusan nekat ini biasanya dibuat berdasarkan sampul album, insting pribadi dan rekomendasi orang lain, atau sepenuhnya ngikutin saran dari mbak-mas penjaga toko/distro.
Videos by VICE
Tentunya kamu tidak selalu beruntung. Bisa aja perkenalanmu dengan Metallica adalah lewat album St. Anger. Duh. Ini bukan salahmu juga kok. Siapa juga yang tau kalau Sandinista! Adalah album The Clash dimana mereka berusaha keluar dari kontrak label rekaman mereka dan tentunya bukan album terbaik band punk ikonik tersebut? Tenang aja, gak usah malu, karena album-album beginilah yang justru kerap menjadi jembatan penghubung antara anda dengan rilisan klasik band-band tersebut. Bisa aja malah album yang kurang bagus membuka jalan ke semesta musik baru yang belum pernah kalian telusuri.
Ada hubungan aneh yang kerap terbentuk antara pendengar dengan album pengantar ke sebuah band, tidak peduli apakah ini album “klasik” mereka atau bukan. Cinta pertama itu sulit dilupakan, tidak peduli betapa memalukan ketika diingat. Nah berikut adalah beberapa album yang menjadi cinta pertama staf Noisey, walaupun secara obyektif kini bisa kita bilang album-album tersebut busuknya bukan main. Apa album-album yang kalian dengar pas masih perjaka soal musik dan bikin kalian mengenal band legendaris? Kalau versi kami, ini 12 di antaranya:

Weezer – The Green Album
Pengennya sih saya bisa bilang album yang membangkitkan musikalitas remaja adalah album kanonikal macam Dookie-nya Green Day atau London Calling-nya The Clash. Tapi pada kenyataannya, saya dulu adalah seorang bocah aneh pemalu. Ayah saya tidak mendengarkan musik apapun yang dirilis setelah 1974 kecuali Bruce Springsteen. Ibu saya malah tidak peduli dengan musik. Mau tidak mau, saya harus mencari edukasi musik sendiri. Ketika berumur 13 tahun, rak CD saya sudah berisikan album klasik macam Third Eye Blind dan No Strings Attached. Suatu siang, saya berjalan ke toko musik terdekat dan berniat membeli album Writing on the Wall milik Destiny’s Child, namun tidak sengaja melihat poster hijau neon bertuliskan Weezer. Selain pernah menonton video musik “Hash Pipe” di MTV, saya tidak tahu apa-apa soal mereka.
Saya nekat membeli album mereka dan hidup saya tidak pernah sama setelah itu. Apabila Beyonce dan kedua saudarinya memuaskan gairah saya untuk musik dance pop, musik Weezer berhasil berbicara langsung dengan sisi canggung saya sebagai remaja. Tanpa referensi musik “indie” sama sekali, Green Album menjadi semacam narkoba pertama saya ke dalam dunia rock ‘n’ roll: musiknya catchy, ngerock, tapi tidak ribet. Saya langsung terobsesi. Gak usah ngomongin lirik Rivers yang membosankan dan gak masuk akal, karena pas umur segitu, otak saya belum nyampe. Yang berhasil menggerakan hati saya adalah emosi dari melodi lagu-lagu mereka. Tidak lama kemudian saya mulai mengulik album-album awal Weezer yang lebih kompleks, Blue dan Pinkerton, yang juga gak santai kerennya. Dari situ saya mulai merambah ke the Pixies, kemudian jadi dengerin punk, blues, dan seterusnya. —Andrea Domanick

The Misfits – American Psycho
Sama seperti kebanyakan bocah berumur 13 tahun yang ingin masuk ke dunia punk, saya membeli beberapa album dari band punk klasik macam Dead Kennedys, Minor Threat, The Misfits. Minor Threat mah gampang karena mereka cuman punya satu album. Saya beruntung dengan DK, kebetulan membeli album Fresh Fruit, nah sayangnya buat The Misfits, saya membeli album mereka paling baru saat itu, American Psycho. Insert booklet albumnya bisa dibuka menjadi poster yang kemudian saya tempel di tembok. Musiknya? Ehh yaaaa boleh juga. Kan Misfits band punk klasik? Saya harus suka dong.
Sesungguhnya hati kecil saya menyadari bahwa album ini payah—banyak sound harmonisasi ala Metallica—tapi kan ini The Misfits lho! Masak iya anak-anak punk bermohawk dengan tempelan patches dimana-mana salah selera musiknya? Tapi ternyata saya yang salah. Semua penggemar sejati Misfits menganggap di American Psycho, Misfits sudah lewat masa keemasannya. Ketika akhirnya saya membeli box set Misfits berisikan album Earth A.D., Static Age, Evilive, baru deh saya ngerti hypenya! Danzi! Nah ini baruuu Misfits betulan. Setelah itu saya mengulik katalog awal Misfits dan tidak pernah kembali ke album-album baru. Hingga sekarang, saya masih sering mengejek American Psycho biarpun sebetulnya saya masih hafal lirik satu album. —Dan Ozzi

Liz Phair – Liz Phair
Saya ingat sengaja tinggal lebih lama di bioskop untuk membaca kredit film Win A Date with Tad Hamilton hanya untuk mendapatkan nama musisi yang membawakan lagu “Why Can’t I?” Ternyata lagu ini bisa ditemukan di album pop self-titled sampah Liz Phair yang dirilis di 2003, diproduksi oleh tim yang juga bekerja sama dengan Britney Spears dan Avril Lavigne. Penggemar dan kritikus musik membenci album ini. Bahkan The New York Times mengatakan Phair telah melakukan “bunuh diri karir yang memalukan.” Ya mana gue tau? Waktu itu lagi demen-demennya musik rock cewe macem Fe Fe Dobson, Avril, dst. Tapi tenang, setelah fase itu lewat, saya langsung menyelam ke dunia grunge-pop nyentrik macam Juliana Hatfield, That Dog dan tentunya Liz Phair era Exile in Guyville, yang sekarang menjadi salah satu album favorit saya sepanjang masa. Tapi hingga sekarang pun saya masih mendengarkan lagu “Why Can’t I” setiap habis ditolak cowok. —Bryn Lovitt

The Stone Roses – The Second Coming
Saat itu 1994. Musik yang populer di AS kala itu Wu-Tang Clan, Snapcase, Fugazi dan apapun yang berbau punk. Saya sudah melalui fase “alternatif klasik” saya dan masih menyukai band-band seperti The Cure, New Order, dan lainnya, tapi belum mengeksplor lebih jauh. Setelah mendengar banyak hal positif tentang Stone Roses, saya memutuskan untuk memberi musik mereka kesempatan.
Ketika The Second Coming dirilis 5 tahun paska album self-titled, album tersebut mendapat promosi gila-gilaan lewat single mantap “Love Spreads” yang menampilkan aksi gitar slide. Lagu ini mulai diputar di radio, kemudian video musik menyusul. Setelah merasa “mengerti” musik mereka, saya menuju toko musik setempat dan membeli kopi album tersebut. Ini keputusan buruk. Beberapa bulan kemudian, seorang teman melihat CD The Second Coming saya dan mengatakan, “Elo beli itu? Dengerin album pertama kali!” Saking buruknya, album ini menjadi bahan olok-olok di salah satu adegan terbaik film Shaun of the Dead. —Fred Pessaro

Ryan Adams – Rock n Roll
Setelah lulus kuliah, saya kembali pindah ke rumah dan mengalami masa-masa buruk. Setelah serangan teror 9/11, sulit untuk mencari pekerjaan dan saya terpaksa bekerja di bidang retail, diperas tenaganya dan digaji kecil. Saking sibuknya, saya tidak memiliki kehidupan sosial di luar bermain video game. Kehidupan saya menyedihkan dan dramatis, maka tidak heran saya menyukai musik yang sedih dan dramatis. Demi nostalgia, saya mulai memutar kembali musik-musik galau yang sering diputar teman-teman di zaman kuliah: Wilco dan Ryan Adams. Di 2003, Adams menyalurkan sisi glam rock ironiknya di album Rock n Roll, dan entah kenapa musiknya nyangkut di kepala. Saya suka banget dengan lagu-sok-senang-tapi-sebetulnya-galau-banget “So Alive,” yang kedengeran seperti Rufus Mainwright yang sedang nyanyi di kontes karaoke U2. Ya memang inilah masa-masa rendah dalam hidup. Untungnya beberapa tahun kemudian saya semakin ahli mencari musik depresif ( Pornographynya The Cure dong!) dan Ryan mulai mengurangi porsi rock musiknya dan kembali memainkan musik moody. —Craig Jenkins

Slipknot – Iowa
Saya berumur 14 dan penuh amarah saat album ini diliris pada 2001. Melihat kebelakang, saya juga gak ngerti kenapa saya segitu marahnya sampe doyan nonjok tembok, ribut sama temen sekolah dan dipaksa ikut kelas anger management. Mungkin ini tipikal kemarahan remaja yang kebetulan keluar dalam bentuk agresifitas. Ya apapun itu, perlu ada soundtrack yang mengiringi. Melalui teman-teman yang hobi main ke Hot Topic, saya menemukan musik yang sempurna untuk menemani sikap kurang ajar saya ketika remaja: Slipknot. Saya tertarik dengan album kedua mereka, Iowa, dengan sampul berwarna biru dan perak menyala dan judul-judul lagu nyolot seperti “People = Shit” dan “The Heretic Anthem.” Memang sekarang album ini terdengar murahan untuk saya yang sudah menghabiskan 13 tahun terakhir mendengarkan musik metal, tapi di saat itu, ini adalah musik paling ekstrem yang pernah menghampiri kuping saya—semacam pembuka jalan bagi ketertarikan saya dengan death metal, sebelum akhirnya mengarah ke grindcore, black metal, doom dan crust punk. Fase nu-metal saya memang tidak bertahan lama, tapi saya tidak bisa memungkiri bahwa dialah yang membuka jalan saya ke musik ekstrem lainnya. —Kim Kelly

Bob Dylan – Self Portrait
Dirilis pada 1970 di tengah dua album klasik Nashville Skyline dan New Morning, album Self Portrait milik Bob Dylan tidak diterima dengan ramah oleh para kritikus. Singkatnya, semua orang menganggap album ini sampah. Album berkonsep tentang melihat ke dalam diri dan bagaimana kita menghadapi imej kita sebagai manusia dibenci secara universal. Beberapa penulis musik rock (sudah pasti berkulit putih) menyatakan album ini adalah tanda akhir dari era 60an, melebihi bubarnya The Beatles. Faktanya, resensi legendaris Greil Marcus di Rolling Stone memulai artikelnya dengan frasa sederhana: “Anjing, musik sampah apaan nih?” Waktu itu bukan era yang bahagia bagi Bob Dylan.
Respon negatif ini akurat apabila anda hanya peduli tentang memiliki opini yang diterima masyarakat. Saya juga tidak akan mengatakan Self Portrait lebih bagus dibanding lagu-lagu luar biasa lainnya yang diproduksi Bob Dylan sepanjang karirnya. Saya juga masih berumur -17 tahun ketika album ini dirilis. Namun menurut analisa ngasal saya, rasanya para kritikus bereaksi berlebihan karena Dylan tidak menulis album seperti yang mereka inginkan. Self Portrait terasa santai, berantakan dan tidak lengkap. Vokalnya gak karuan, dan ngos-ngosan, riff gitar berantakan, dan penulisan lagu tidak fokus. Namun semua kualitas ini jugalah yang membuat album ini menonjol ketika saya dengarkan pertama sekali sebagai anak kecil. Tentunya ini bukan perkenalan saya dengan Bob Dylan—mustahil anda lahir di Midwest, AS dan tidak pernah mendengar musik Dylan—namun inilah album pertama yang mengenalkan saya ke dunia Dylan, penuh dengan eksplorasi diri dan berusaha memahami peran kita di dunia. Album ini mengajarkan bahwa saya tidak harus menjadi sempurna. Tidak ada yang sempurna. Musik yang sempurna itu membosankan. Self Portrait tidak mencoba menjadi sempurna—hanya menjadi manusiawi. Gak enak kan mesti menyadari kekurangan diri?
—Eric Sundermann

Nine Inch Nails – With Teeth
Ketika kelas 6 SD, entah kenapa, saya kesengsem dengan dunia goth. Saya suka Marilyn Manson, Jeff Hardy dan sering membeli buku acak tentang cara membangkitkan arwah seseorang. Seru deh. Jadi tidak heran akhirnya saya menemukan Nice Inch Nails lewat rilisan 2005 mereka, With Teeth, album pertama mereka semenjak 1999. Sekarang saya sadar bahwa album itu tidak menggigit sama sekali. Album-album mereka sebelumnya memiliki elemen yang membuat Nine Inch Nails keren: semacam sikap masa bodo dibelakang semua peralatan dan bebunyian elektronik. Namun di With Teeth, NIN terasa seperti band rock alternatif dari episode Law and Order: SVU. Lagu-lagunya membosankan, dan sangat basic. Seolah-olah Trent Reznor berusaha menulis lagu pop, atau mencoba mengulang kembali kesuksesan “Hurt.” Ya paling enggak DVD Live mereka keren lah.—John Hill

Green Day – American Idiot
Sebelum saya mulai, anda harus tahu bahwa sebagai bocah berumur 13 tahun dari kota kecil, biarpun saya memiliki koneksi internet, saya belum mengerti cara menggunakannya. Saya tahu tentang Green Day hanya karena sepupu saya yang lebih asik pernah mengenakan kaos Dookie. Saya enggak tau kenapa album pertama yang saya beli justru American Idiot. Parahnya lagi, saya sebetulnya suka banget album ini; saya mungkin udah dengerin album ini 100 kali. Transisi chorus ke bagian cepat dan heavy di “Are We the Waiting/St. Jimmy” sangat empuk di kuping, dan tentunya sebagai seorang remaja depresi, “Wake Me Up When September Ends,” gue banget gitu lah. Saya tidak akan pernah melupakan hari ketika seorang bocah lelaki gebetan bertanya CD apa yang sedang saya dengarkan di Sony Walkman (gak punya duit buat iPod). Dengan bangga saya menjawab “album baru Green Day.” Dia langsung mengatakan album itu sampah dan Green Day belum merilis album bagus semenjak Nimrod. Saya buru-buru berbohong dan mengatakan itu CD teman yang baru saya pinjam. Selepas sekolah, saya buru-buru membeli CD Nimrod. —Annalise Domenighini
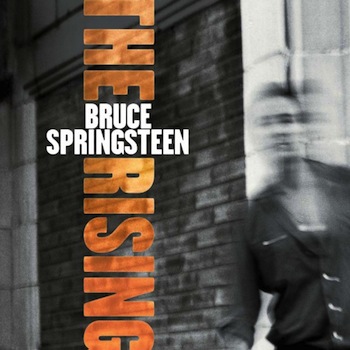
Bruce Springsteen – The Rising
The Rising merupakan album comeback Bruce Springsteen, rilisan pertamanya dalam 7 tahun semenjak album gagal The Ghost of Tom Joad. Ini juga rilisan pertamanya bersama E Street Band selama lebih dari 10 tahun. Album ini diriis tanggal 11 September, di saat AS sedang butuh-butuhnya semacam ekspresi patriotik yang bisa menyatukan penduduknya. Album ini ngehit berat, dan memperkenalkan The Boss ke generasi penggemar baru yang mungkin tidak pernah mendengarkan rilisan klasiknya dari 70an dan 80an. Beberapa tahun kemudian, Springsteen menjadi bagian dari ledakan indie rock di pertengahan 2000an, melakukan sederetan tur besar dan memperbarui statusnya sebagai ikon politik di dunia musik.
Namun biarpun The Rising merupakan pilihan album Springsteen yang tepat di saat itu, ceritanya beda lagi kalau kita ngomongin sepanjang masa. Album ini membosankan. Banyak lagunya kelewat mengandalkan chorus anthemic, dan tidak memiliki ketegangan dan kompleksitas yang membuat penulisan lagu Springsteen bagus. Nih, saya jujur aja deh: Banyak orang takut dicap anti-Amerika untuk mengatakan mereka tidak suka album ini. Para kritikus pun tidak berani bersikap kritis. “Empty Sky” berhasil menangkap perasaan hancur paska serangan 9/11. “My City of Ruins” memang lagu yang luar biasa kuat, tapi ini pengecualian di tengah lagu-lagu tidak bermutu seperti “Worlds Apart.” The Rising Tour merupakan konser pertama saya—dengan Ayah—dan hingga hari ini merupakan salah satu konser terbaik dalam hidup. Tapi The Rising adalah salah satu album Springsteen paling tidak subtil dan tidak menyenangkan karena terlalu terfokus dengan ide kolektifitas dan bersifat tidak universal seperti album-album klasik lainnya. Memang album ini berhasil membawa AS kembali masuk dalam genggaman Springsteen dan ini layak dihargai, tapi tetap saja ini titik perkenalan yang aneh untuk masuk ke dalam diskografi salah satu musisi terbaik AS. —Kyle Kramer
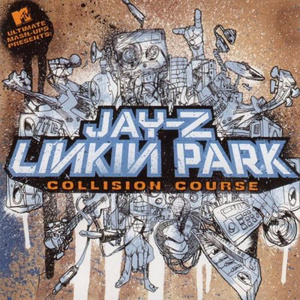
Jay Z / Linkin Park – Collision Course
Kebanyakan orang masih bego di umur 14. Misalnya, dulu saya penggemar Linkin Park. Campuran musik gitar, rap dan anime terasa sangat unik bagi saya. Suatu hari, ketika sedang mengunduh lagu, saya menemukan sebuah lagu Linkin Park yang memiliki bagian rapping luar biasa. Saya mengecek informasi lagu dan kaget menemukan sebuah nama yang tidak saya kenali: Jay-Z. Saya baru saja mengunduh Collision Course dan pengenalan saya dengan rapper terbaik sepanjang masa baru saja dimulai. Setelah mendengarkan album, saya menyimpulkan gaya rap cair Jay-Z lebih baik dibanding vokal patah-patah Chester. Setelah bosan dengan Collision Course, saya mulai menjajal The Black Album. Jay Z membuka sebuah dunia baru penuh mitos dengan dirinya sendiri sebagai karakter sentral dan saya seperti ditarik untuk mencari tahu setiap informasi tentang si karakter. Lambat laut cinta saya untuk Linkin Park memudar dan saya mengulik sejarah Jay Z, mencari tahu tentang setiap proyek kolaborasi yang dia lakukan. Makasih ya Linkin Park sudah membuka jalan saya untuk bertemu dengan Jay Z. Paling enggak ini satu hal baik yang kalian pernah lakukan. —Slava Pastuk

Guns N’ Roses – Use Your Illusion I & II
Ketika Guns N’ Roses merilis album dobel ambisiusnya di September 1991, saya masih mendengarkan “I Love Your Smile”nya Shanice dan “Around The Way Girl” milik LL Cool J. Saya baru saja meninggalkan San Francisco dan pindah ke Belanda dan kerap kangen mendengarkan lagu-lagu R&B/hip-hop dari tanah air tercinta. Waktu itu mah, saya kirain Bon Jovi heavy metal.
Setahun kemudian, Ibu, Ayah angkat dan saya pindah ke Southampton, Inggris dan saya kerap nongkrong bersama gerombolan anak-anak di sekolah yang dijuluki “hippies.” Kami hobi mengenakan Doc Marten dan flannel. Kami gak suka pake shampoo karena rambut semi-gondrong ala Cobain kami entar rusak. Saya mulai melupakan Boys II Men dan mendengarkan Nirvana, Ugly Kid Joe, Metallica dan Blind Melon. Lucunya, band yang dibenci Nirvana, Guns N’ Roses juga salah satu favorit kami. Kami sering memutar Use Your Illusion—album ganda yang dirilis terpisah dalam hari yang sama. Ketika album ini dirilis, kami masih berumur satu tahun.
Melihat kebelakang, album ini merupakan 151 menit siksaan penuh dari Axl dan kawan-kawan berambut lebay. Album ini merupakan cerminan setiap keputusan artistik mereka—durasi lagu yang lama, jutaan dollar dihabiskan untuk video musik mewah, ambisi untuk dominasi dunia yang tercermin dalam lagu-lagu soft rock ramah radio penuh hooks. Lagu 10 menit tanpa satupun chorus! Memang mereka bukan sosok-sosok konvensional, tapi akibat berbagai jenis narkoba yang mereka pakai, semua ide dikira jenius kali ya. Gak boleh ada yang dibuang! Namun tetap saja di kala itu, saya suka banget solo gitar lebay Slash dan lengkingan bak kucing dari Axl. Sekarang saya hanya bisa meringis memikirkan noraknya merilis 30 lagu dalam satu hari. Selain “November Rain,” “Civil War,” riff keren di “You Could Be Mine,” dan beberapa lagu lainnya, dua album ini penuh dengan filler yang seharusnya dibuang saja. Mengingat pada 1987 saya masih mendengarkan Salt-N-Pepa dan Madonna, perkenalan saya dengan GN’R dimulai via IYI sebelum akhirnya saya mengulik Appetite for Destruction, album debut yang luar biasa galak dan salah satu album rock terbaik di 80’an. —Kim Taylor Bennett
More
From VICE
-

(Photo by Francesco Castaldo/Pacific Press/LightRocket via Getty Images) -

M Scott Brauer/Bloomberg via Getty Images -

Firefly Aerospace/YouTube -

Justin Paget / Getty Images
